Buku "Teruslah Bodoh! Jangan Pintar" karya Tere Liye menyuguhkan sindiran tajam dan refleksi kritis tentang manusia modern. Simak ulasan lengkapnya di sini.
Teruslah Bodoh! Jangan Pintar adalah salah satu buku nonfiksi terbaru dari Tere Liye yang berisi kumpulan tulisan pendek, refleksi, sindiran, dan kritik sosial yang tajam namun menghibur.
Buku ini bukan buku motivasi biasa. Isinya adalah serangkaian “tamparan halus” bagi para pembaca yang merasa sudah pintar, namun masih terlena oleh ilusi kepintaran di zaman digital.
Latar belakang judul 'Teruslah Bodoh Jangan Pintar' karya Tere Liye
Novel terbaru Tere Liye, 'Teruslah Bodoh! Jangan Pintar', hadir sebagai karya yang sangat relevan dalam konteks dinamika sosial dan politik kontemporer di Indonesia. Buku ini sangat relevan dengan dinamika sosial dan politik kontemporer di Indonesia. Dirilis pada tanggal 1 Februari 2024, di tengah masa kampanye politik yang gencar, tanggal penerbitan novel ini secara signifikan berkontribusi pada gaungnya di kalangan masyarakat.
Penerbitannya pada saat yang penting ini memicu diskusi yang luas di media sosial, mendorong novel ini menjadi trending topic. Hubungannya yang kuat dengan isu-isu terkini, terutama di bidang politik dan hukum, menarik perhatian pembaca, banyak di antara mereka yang merasa bahwa novel ini “sangat relevan dengan isu-isu yang kita hadapi” dan mengatakan bahwa novel ini membuat hati mereka terenyuh untuk rakyat Indonesia.
Perilisan novel ini bertepatan dengan musim kampanye, dan segera memicu diskusi yang luas. Hal ini menunjukkan pilihan strategis yang matang oleh penulis atau penerbit. Pilihan ini berhasil menangkap sentimen publik yang sedang berkembang dan wacana politik yang memanas.
Hal ini menunjukkan bahwa novel ini tidak hanya berfungsi sebagai karya fiksi, tetapi juga sebagai komentar sosial yang tepat waktu yang dirancang untuk beresonansi dengan kegelisahan sosial-politik yang ada di Indonesia. Hal ini meningkatkan status novel ini dari sekadar hiburan menjadi sebuah artefak budaya penting yang secara aktif berpartisipasi dan merefleksikan keprihatinan masyarakat kontemporer Indonesia, bertindak sebagai cermin dan katalisator untuk diskusi publik mengenai isu-isu penting seperti korupsi, dinamika kekuasaan, dan kondisi keadilan di Indonesia.
Daya tarik novel ini semakin diperkuat dengan judulnya yang provokatif dan satir: 'Tetaplah Bodoh! Jangan Pintar." Judul ini dirancang untuk menantang persepsi konvensional tentang kecerdasan dan kesuksesan dan telah dikenal memicu keheranan di antara para pembaca yang bertanya, "Aneh. Mengapa harus menjadi orang bodoh? Ironisnya, novel ini mendefinisikan ‘bodoh’ bukan sebagai ketiadaan pengetahuan atau kecerdasan, tetapi sebagai ketiadaan ambisi dan keserakahan.
Sebaliknya, ‘individu yang cerdas dan berpendidikan menjadi bagian dari kekacauan’. Ini adalah kritik tajam terhadap kecerdasan yang tidak memiliki moralitas dan kebijaksanaan sejati. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebijaksanaan dan kecerdasan, mendorong mereka untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang lebih mendasar seperti kebaikan, kejujuran, dan moralitas daripada mengejar pengetahuan yang dangkal. Dengan demikian, judul buku ini bertindak sebagai pernyataan tesis, mendorong pembaca untuk mempertimbangkan kembali definisi konvensional tentang ‘pintar’ dan ‘bodoh’ dalam konteks sosial dan etika.
Judul 'Tetaplah Bodoh! Jangan Pintar." adalah sebuah perangkat ironis yang menantang nilai-nilai sosial konvensional. Judul ini menjadi latar bagi kritik novel ini terhadap ‘kecerdasan tanpa kebijaksanaan’ dan ‘kepintaran yang dangkal’. Judul ini lebih dari sekadar judul yang menarik perhatian; judul ini merupakan pernyataan tesis tematik yang mempersiapkan pembaca untuk menghadapi sikap kritis novel ini.
Dengan menggunakan judul yang berlawanan dengan intuisi dan menantang, Tere Liye memaksa pembaca untuk mempertimbangkan kembali persepsi mereka tentang apa artinya menjadi ‘pintar’ atau ‘bodoh’. Hal ini membangun nada kritis dan reflektif sejak awal, menandakan bahwa buku ini akan mengeksplorasi dimensi moral dan etika dari kecerdasan, bukan hanya aspek intelektualnya.
Judul ini secara langsung menantang masyarakat yang sering memprioritaskan kecakapan intelektual dan kesuksesan materi di atas integritas dan hati nurani.
Tentang novel dan karakter utama
Teruslah Bodoh! Jangan Pintar merupakan kumpulan esai singkat dan refleksi sosial yang diluncurkan Tere Liye pada tahun 2023. Berbeda dengan novel-novelnya yang berlatar fantasi dan petualangan, di sini Tere Liye menyajikan gaya bahasa satir untuk menyoroti budaya “pamer pintar” di era digital.
Penting untuk mengingat klasifikasipembaca pada novel ini adalah pembaca 18+, mengingat tema dan konten novel yang berat. Meskipun tidak ada adegan vulgar, merokok, atau penggunaan narkoba, beberapa bab berisi adegan kekerasan, kelicikan, kejahatan, dan kemartiran yang lebih cocok untuk pembaca dewasa.
Novel ini memiliki narasi berlapis dengan dua alur cerita yang saling melengkapi yang menyampaikan pesan utama.
Karakter Utama
Sebenarnya Teruslah Bodoh! Jangan Pintar bukanlah sebuah novel fiksi, melainkan kumpulan esai nonfiksi. Karena itu, buku ini tidak menghadirkan “karakter” dalam pengertian tokoh cerita—tidak ada protagonis, antagonis, ataupun tokoh pendukung ala novel.
Namun jika kita mau mengibaratkan elemen “tokoh” dalam esai–esai reflektif ini, maka:
Suara Narator (Tere Liye)
– Berperan sebagai “pencerita” yang menyentil dan menantang pembaca.
– Menggunakan gaya satir dan retoris untuk membuat pembaca bertanya, “Apakah saya benar‑benar paham?”
“Anda” sebagai Pembaca
– Di setiap tulisan, “Anda” (pembaca) diundang masuk sebagai tokoh utama—yang diuji kerendahan hati dan kejujurannya.
– Esai‑esai tersebut ‘berdialog’ langsung dengan Anda, mendorong refleksi pribadi.
Namun kita bisa dapatkan karakter narasi filosofis yang bercerita tentang tokoh bernama Ali pada buku ini. Salah satu inti cerita berpusat pada seorang pemuda bernama Ali yang tinggal di sebuah desa kecil. Ia digambarkan sebagai seorang pemuda yang cerdas dan memiliki cita-cita yang tinggi untuk meraih kesuksesan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa dunia tidak selalu adil dan orang yang pintar dan berpendidikan belum tentu mencapai kesuksesan yang mereka inginkan.
Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria tua misterius yang memberikan pencerahan. Orang tua itu mengungkapkan bahwa dunia sedang dalam kekacauan dan orang-orang yang pintar dan berpendidikan adalah bagian dari kekacauan ini.
Dia kemudian mengajarkan Ali tentang pentingnya menjadi 'bodoh', yang dalam konteks ini bukan berarti tidak memiliki pengetahuan atau kecerdasan, melainkan tidak memiliki ambisi dan keserakahan. Ali mulai menerapkan filosofi ini dalam hidupnya: ia berhenti mengejar kesuksesan materi dan mulai fokus pada hal-hal yang lebih esensial, seperti keluarga dan teman.
Seiring berjalannya waktu, ia menemukan bahwa hidupnya menjadi lebih bahagia dan damai, bebas dari stres dan beban ambisi. Narasi ini menjadi kerangka filosofis yang mendasari makna judul dan tema utama novel ini, yang menekankan bahwa nilai-nilai non-materialistik adalah kunci kebahagiaan sejati.
Narasi Utama
Plot utama novel ini berlatar belakang masa depan, ketika masyarakat terbagi menjadi dua kelas: 'orang pintar', yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, dan 'orang bodoh', yang ditindas dan dieksploitasi. Namun, Tere Liye dengan cermat menunjukkan bahwa tidak semua orang pintar itu korup. Masih banyak orang yang baik hati dan berani melawan sistem. Namun, ada juga yang menggunakan kepintaran mereka untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Latar distopia ini berfungsi untuk memperkuat kritik sosial terhadap ketidaksetaraan yang merajalela dan penyalahgunaan kekuasaan.
Konflik utama novel ini berpusat pada perjuangan sengit sekelompok aktivis lingkungan. Bertekad untuk menggagalkan izin konsesi PT Semesta Minerals & Mining, sebuah perusahaan tambang besar yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan kerugian besar, termasuk korban jiwa, selama beberapa dekade, mereka memulai misi untuk mengungkap kesalahan perusahaan tersebut. Perjuangan para aktivis berlangsung di ruang sidang tertutup, di mana mereka berusaha menghadirkan kesaksian dari orang-orang yang hidupnya secara langsung dipengaruhi oleh operasi perusahaan. Ruang sidang menjadi arena pertarungan antara kebenaran dan manipulasi hukum.
Para aktivis harus menghadapi Hotma Cornelius, seorang pengacara yang kuat dan spesialis pembela kejahatan. Ia digambarkan sangat terampil dalam mendiskreditkan saksi dan menciptakan suasana yang mengintimidasi di ruang sidang. Dia melambangkan gagasan bahwa hukum dapat dibeli dan disalahgunakan oleh orang kaya. Alur cerita novel ini bergerak maju mundur dan disajikan melalui serangkaian kesaksian para saksi, seperti kesaksian Amad, yang mengungkapkan masa lalu kelam mereka dan penderitaan yang diakibatkan oleh operasi perusahaan tambang. Struktur naratif ini memungkinkan novel ini menyajikan berbagai perspektif dan menunjukkan kedalaman dampak dari isu-isu yang kompleks.
Novel ini dengan jelas mengangkat isu-isu sensitif seperti hakim yang menyetujui pembukaan lahan baru dengan imbalan suap, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan gaji, dan penggunaan tenaga kerja asing untuk pekerjaan pertanian, di mana perusahaan-perusahaan dengan seenaknya mendorong karyawan yang tidak puas untuk mengundurkan diri. Meskipun Tere Liye menyatakan bahwa cerita ini murni fiksi, banyak pembaca yang merasa bahwa narasinya sangat detail dan terasa 'sangat relevan' dengan kondisi nyata di Indonesia, seperti isu pertambangan nikel saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa novel ini secara efektif mencerminkan realitas sosial dan ekonomi yang kompleks di Indonesia.
Adanya dua rangkuman cerita yang berbeda-perjalanan filosofis Ali dan konflik antara para aktivis dan perusahaan tambang-menunjukkan adanya struktur naratif yang berlapis. Kisah Ali, di mana ia mendefinisikan 'bodoh' sebagai ketiadaan ambisi dan keserakahan, kemungkinan besar berfungsi sebagai kerangka filosofis atau latar belakang tematik untuk perjuangan para aktivis.
Hal ini memperkuat konsep 'bodoh' sebagai antitesis dari keserakahan dan ambisi yang digambarkan dalam konflik yang lebih luas. Pendekatan naratif ganda ini memungkinkan novel ini untuk beroperasi pada tingkat introspektif pribadi - mengeksplorasi makna sebenarnya dari 'pintar' atau 'bodoh' bagi kesejahteraan individu - dan tingkat sosial yang lebih luas, yang menunjukkan bagaimana filosofi ini dapat diterapkan pada isu-isu sistemik seperti korupsi, eksploitasi lingkungan, dan ketidakadilan sosial. Hal ini memperkaya kedalaman dan resonansi tematik novel ini.
Penggambaran taktik ruang sidang yang mendetail, terutama kemampuan pengacara pembela (Hotma Cornelius) untuk 'mematahkan kesaksian' dan 'membuatnya melekat', menyoroti isu krusial tentang manipulasi kebenaran dan keadilan di dalam sistem hukum. Ini bukan sekadar pertarungan hukum, namun merupakan representasi simbolis tentang bagaimana kekuasaan dan kekayaan dapat memutarbalikkan kenyataan dan melemahkan keluhan yang sah, mengubah proses hukum menjadi alat penindasan dan bukannya keadilan.
Keberhasilan pengacara dalam 'mematahkan kesaksian' menunjukkan bagaimana teknis hukum, kecakapan retorika, dan manuver strategis dapat membayangi kebenaran dan keadilan. Hal ini menyiratkan adanya kelemahan sistemik yang mendalam di mana 'kepintaran' hukum digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan, yang secara langsung bertentangan dengan tema utama novel ini, yaitu kebijaksanaan sejati yang lebih unggul daripada ambisi dan keserakahan. Rasa frustrasi yang mendalam yang diungkapkan oleh para pengulas ('Saya ingin meninju pojokan') menyoroti dampak emosional dari penggambaran ini terhadap para pembaca, yang membuat kritik terhadap kerentanan sistem hukum terhadap korupsi menjadi lebih kuat.
Akibatnya, latar ruang sidang menjadi mikrokosmos dari masyarakat yang korup, di mana 'kebenaran' bukanlah realitas objektif, melainkan konstruksi yang mudah dibentuk dan didistorsi oleh pengaruh finansial dan pengaruh politik. Hal ini memperkuat pesan utama novel ini tentang bahaya menjadi 'pintar' (mampu secara intelektual) tanpa 'hati nurani' dan landasan etika.
Inti dari kritik novel ini terletak pada interpretasi ironisnya terhadap 'kebodohan' dan 'kepintaran'. 'Kebodohan' tidak diartikan sebagai kurangnya pengetahuan atau kecerdasan, tetapi lebih kepada ketiadaan ambisi dan keserakahan. Sebaliknya, 'orang yang pintar dan berpendidikan adalah bagian dari kekacauan'.
Ini adalah kritik mendalam terhadap paradigma kesuksesan modern yang sering kali mengabaikan moralitas. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebijaksanaan dan kecerdasan, mendorong mereka untuk mempertimbangkan nilai-nilai seperti kebaikan, kejujuran, dan moralitas daripada sekadar mengejar pengetahuan.
Novel ini menantang pembaca untuk menyadari bahwa 'kecerdasan' yang sebenarnya harus mencakup kematangan emosional dan spiritualitas, bukan hanya kemampuan teknis atau akademis. 'Kebodohan positif' digambarkan sebagai sikap keterbukaan untuk terus belajar dan kerendahan hati dalam mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Sikap ini merupakan antitesis dari kesombongan intelektual yang sering kali menjadi akar dari masalah-masalah sosial.
Penggambaran ‘kebodohan’ sebagai keadaan yang bebas dari ambisi dan keserakahan, dan ‘kepandaian’ yang berpotensi menyebabkan ‘kekacauan’ atau ‘hilangnya nilai-nilai etika dan moral’ dalam novel ini, memberikan kritik sosio-moral yang mendalam terhadap meritokrasi modern dan kapitalisme yang tak terkendali. Novel ini menunjukkan bahwa pemujaan masyarakat terhadap ‘kecerdasan’ (yang sering disamakan dengan kesuksesan materi dan kekuasaan) secara paradoks dapat mengakibatkan kerusakan moral dan ketidakadilan sistemik. Oleh karena itu, novel ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendasar untuk mengevaluasi kembali apa yang dimaksud dengan kemajuan masyarakat dan kebajikan individu.
Individu “pintar” yang menjadi “bagian dari kekacauan” adalah mereka yang menggunakan kepintarannya semata-mata untuk keuntungan pribadi. Hal ini secara langsung mengarah pada korupsi dan perusakan lingkungan yang digambarkan dalam narasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dirancang untuk menghargai “kecerdasan” (misalnya, lembaga pendidikan dan struktur perusahaan) dapat secara tidak sengaja mendorong kebangkrutan moral jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, empati, dan pertimbangan etika.
Novel ini berargumen bahwa “kebijaksanaan” (atau “kebijaksanaan hati”) yang sebenarnya berakar pada empati, kerendahan hati, dan integritas-kualitas yang secara ironis diasosiasikan dengan “kebodohan” dalam pengertian satir novel ini. Kritik tematik ini melampaui moralitas individu, menawarkan analisis pedas terhadap masyarakat yang memprioritaskan pencapaian intelektual dan akumulasi materi di atas segalanya.
Novel ini menunjukkan bahwa sistem seperti itu secara inheren menghasilkan individu-individu “pintar” yang secara moral “bodoh” dan merusak. Novel ini menjadi seruan keras untuk perubahan paradigma mendasar tentang bagaimana masyarakat mendefinisikan, menghargai, dan menumbuhkan kecerdasan. Novel ini mengadvokasi pendekatan holistik yang mengintegrasikan kapasitas intelektual dengan kompas etika yang kuat.
Novel ini secara terbuka menunjukkan bagaimana “hukum dapat dibeli oleh mereka yang memiliki uang”, dengan memberikan contoh hakim yang menerima “gratifikasi” dari perusahaan pertambangan. Hal ini secara langsung mengkritik integritas sistem peradilan. Novel ini menunjukkan bagaimana uang dapat menjadi ujung pisau yang mematikan dan bagaimana kebenaran dapat diputarbalikkan untuk memenuhi kebutuhan apa pun.
Novel ini secara efektif menggambarkan bagaimana kekuasaan dan uang memanipulasi keadilan, menciptakan sebuah realitas di mana “hukum dan kekuasaan digunakan oleh serigala-serigala buas berbulu domba.” Meskipun Tere Liye menyangkal bahwa cerita ini adalah fiksi, banyak pembaca merasa bahwa narasinya mirip dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini yang melibatkan pertambangan dan menegaskan bahwa “ini bukan fiksi, ini kenyataan.” Realisme yang pahit ini membuat novel ini menjadi cerminan yang kuat atas kondisi sosial-politik Indonesia.
Struktur & Isi Novel
- Format: Buku disusun dalam bab-bab pendek (10–20 halaman per bab), memudahkan pembaca mampir sejenak dan merenung.
- Gaya Penulisan: Ringkas, langsung ke inti, dengan sentuhan humor gelap. Tiap bab diakhiri “tamparan halus” berupa pertanyaan retoris atau kutipan kuat.
- Tema Utama: Kritikan terhadap sikap sok tahu, opini tanpa riset, dan perlombaan status di media sosial.
Beberapa Kutipan Kuat:
“Pintar Itu Ringan, Bodoh Itu Berat”
– Menekankan bahwa mengakui ketidaktahuan memerlukan kerendahan hati lebih besar daripada memamerkan kepintaran.
“Komentar Kosong”
– Sindiran terhadap tren meninggalkan komentar panjang tanpa isi substansi di platform online.
“Debat Tanpa Landasan”
– Refleksi soal betapa banyak diskusi publik terjadi tanpa data, sumber, atau logika memadai.
Kelebihan & Kekurangan Buku
Kelebihan
- Menyentil Tanpa Menggurui
- Tere Liye berhasil “menampar” pembaca yang suka sok tahu, namun tetap terasa ringan dan tidak menghakimi secara frontal.
- Gaya Bahasa Efektif
- Kalimat-kalimat pendek dan kutipan tajam membuat pesan mudah diingat dan viral di media sosial.
- Relevansi Tinggi
- Setiap topik sangat dekat dengan fenomena sehari-hari: hoaks, klikbait, hingga “keyboard warrior”.
Kekurangan
- Makna Terlalu Singkat
- Nada Sinis
Siapa yang cocok membaca buku ini?
- Pengguna Aktif Media Sosial: Ingin mengevaluasi ulang cara beropini dan berinteraksi online.
- Pembaca Nonfiksi Ringan: Menyukai bacaan pendek, reflektif, dan mudah dikutip.
- Penggemar Tere Liye: Ingin melihat sisi lain penulis favoritnya di luar genre fiksi.
Kesimpulan
Novel Teruslah Bodoh! Jangan Pintar adalah sebuah novel yang melampaui batas-batas fiksi biasa, yang menyajikan komentar sosial yang tajam dan relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Perilisannya bertepatan dengan periode politik yang krusial, dan judulnya yang provokatif dan ironis secara efektif menarik perhatian publik, memicu diskusi mendalam tentang makna sebenarnya dari “kecerdasan” dan “kebodohan” dalam masyarakat. Novel ini mendefinisikan kembali “bodoh” sebagai ketiadaan ambisi dan keserakahan, sekaligus mengkritik “kepintaran” sebagai sumber kekacauan dan hilangnya nilai-nilai etika.
Novel ini dengan jelas menyoroti isu-isu sistemik seperti korupsi dalam sistem hukum, penyalahgunaan kekuasaan oleh orang kaya, dan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat melalui narasi yang berpusat pada perjuangan para aktivis lingkungan hidup melawan perusahaan pertambangan yang korup. Penggambaran rinci taktik manipulasi ruang sidang dan realisme pahit dari ketidakadilan yang terjadi sangat sesuai dengan pengalaman nyata para pembaca di Indonesia, meskipun dalam bingkai fiksi. Hal ini menjadikan novel ini sebagai refleksi yang kuat dari realitas sosial-politik yang kompleks.
Gaya penulisan Tere Liye yang lugas dan kritis serta struktur narasi nonlinier yang kaya akan perspektif berhasil menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan memicu emosi yang kuat. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai kedalaman karakter, fokus novel ini pada eksplorasi tematik dan kritik sosial tetap kuat, dan secara efektif menyampaikan pesan-pesan penting melalui karakter-karakternya.
Dibandingkan dengan karya-karya Tere Liye sebelumnya, terutama seri Tanah Para Bandit, novel ini menunjukkan intensitas dan keberanian yang lebih besar dalam membahas topik-topik sensitif. Akhir cerita yang realistis dan seringkali tidak memuaskan merupakan pilihan berani dari sang penulis yang menegaskan komitmennya untuk tidak mengaburkan kenyataan pahit dan memaksa pembaca untuk menghadapi kenyataan bahwa keadilan tidak selalu tercapai di dunia nyata.
Secara keseluruhan, “Teruslah Bodoh! Jangan Pintar” adalah sebuah karya yang inspiratif dan menggugah pikiran. Novel ini menghibur dan mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan menumbuhkan hati nurani di tengah tantangan zaman. Novel ini merupakan sebuah ajakan untuk menjadi “cerdas”, yang berarti menjadi cerdas dengan cara yang seimbang dengan kebijaksanaan, integritas, dan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Kecerdasan semacam ini dapat membawa pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan negara yang lebih adil di masa depan.
*******
Referensi yang digunakan dalam ulasan:
- perpustakaan.kuduskab.go.id
- mabhak.sch.id
- gramedia.com
- dav.sumbarprov.go.id
- researchgate.net
- kompasiana.com
- tebuireng.online
- lemon8-app.com
- opacperpustakaan.jogjakota.go.id
- goodreads.com
- repository.ubt.ac.id
- resensiefi.my.id
- thebookielooker.com
| Judul | Rating | Cerita & Ilustrasi | Tebal | Berat | Format | Tanggal Terbit | Dimensi | ISBN | Penerbit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JudulTeruslah Bodoh! Jangan Pintar | Rating5.0 | Cerita & IlustrasiTere Liye | Tebal371 halaman | Berat0.305 kg | FormatSoft Cover | Tanggal Terbit28 Januari 2024 | Dimensi20 x 13.5 cm | ISBN9786238882205 | Penerbit Sabak Grip |


Pesan dari
KATALOG BUKU
Buku pilhan lainnya:
Bingung ingin baca review buku apalagi? Silakan cari disini.
Kamu juga bisa temukan buku lain nya di Katalog Kami
























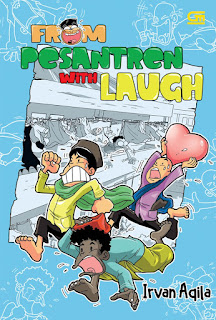
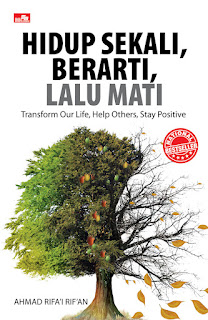











.png)


.png)

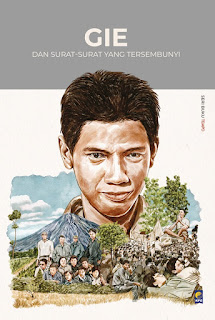





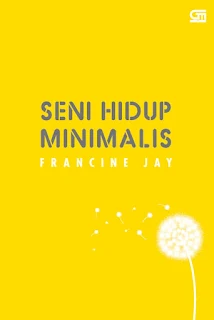









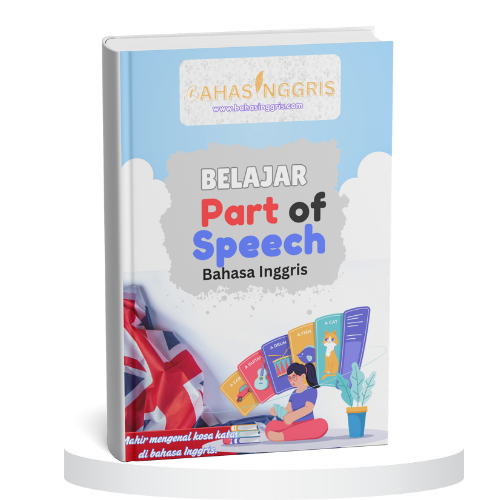























.jpg)







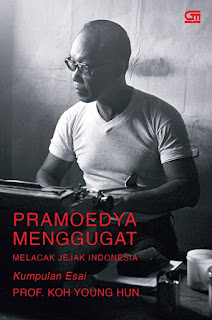


.jpg)



.gif)
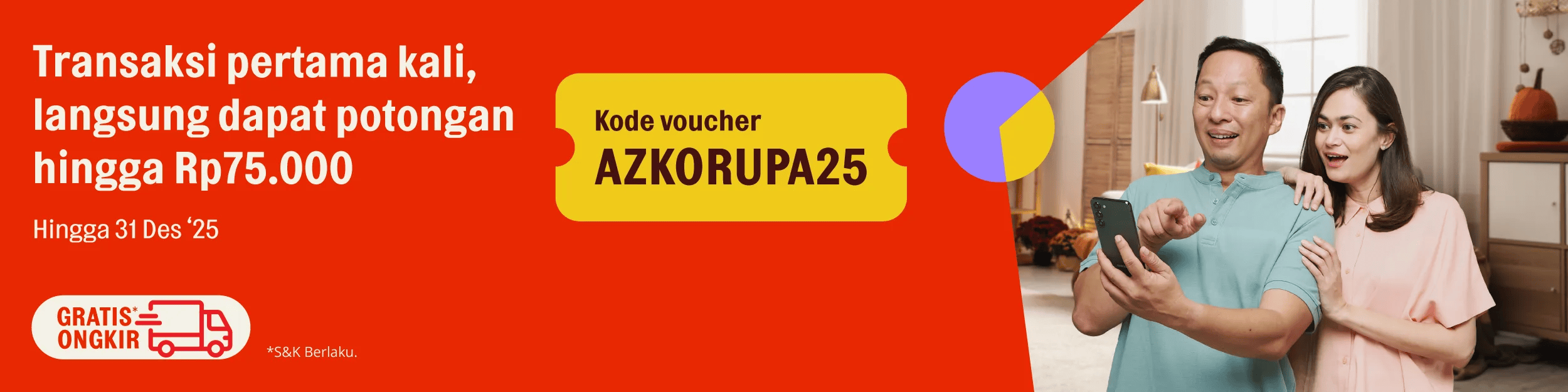

Posting Komentar
0 Komentar